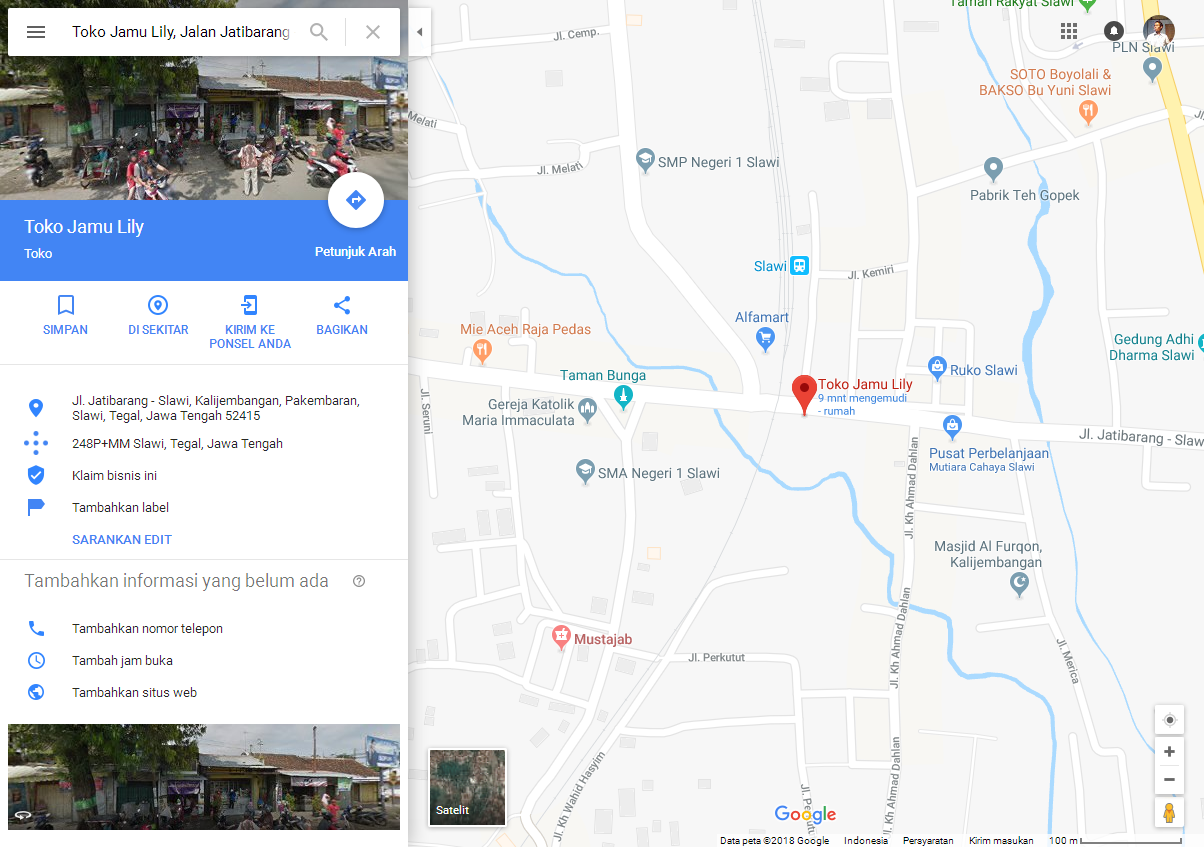Agama Islam adalah suatu aliran dan ajaran yang menginginkan kebahagian, kesempurnaan, dan keselamatan segenap manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan manusia bisa menggunakan ajaran-ajaran Islam untuk memenuhi segala keperluan duniawi dan ukhrawinya.
Dengan mencermati al-Quran, secara sederhana dapat dipahami bahwa Tuhan mengajak hamba-hamba-Nya untuk menjauhkan diri dari penyembahan dunia [segala sesuatu selain Tuhan disebut dunia] dan memperhatikan aspek-aspek spiritual dan alam akhirat.[1] Namun poin ini juga diingatkan bahwa perhatian kepada alam akhirat jangan menjadi alasan untuk memilih bertapa (asketik) dan meninggalkan totalitas aktivitas-aktivitas kehidupan duniawi, melainkan juga tetap memanfaatkan berkah-berkah dan nikmat-nikmat duniawi dengan memperhatikan tolok ukur syariat [hukum fikih] dan senantiasa aktif dan giat dalam kegiatan-kegiatan keseharian dengan tetap berdzikir dan mengingat Tuhan.[2]
Berpijak pada hal ini, seorang Muslim sejati bukanlah penyembah dunia. Ia adalah seseorang yang memanfaatkan nikmat-nikmat Ilahi di dunia demi kesempurnaan ukhrawinya dan meminta kepada Tuhan kebaikan dunia dan akhirat.[3]
Sebagian dari kalangan Muslim ini hanya memikirkan dimensi-dimensi duniawi agama seperti penegakan kedisiplinan umum, pembentukan negara, aktivitas-aktivitas pertanian dan perdagangan, kemajuan ilmu, dan lain sebagainya sehingga terkadang melupakan bahwa semua aspek duniawi agama hanya merupakan suatu pengkondisian dan bekal [bukan tujuan] bagi kehidupan abadi dan cita-cita lebih tinggi [suci] yakni meraih keridhaan Tuhan. Aspek duniawi agama secara mandiri tidak memiliki nilai ukhrawi.
Dan sebagian yang lain hanya menekankan dan memperhatikan sisi-sisi spiritual dan batin Islam, dan dia meletakkan dirinya sendiri di bawah tanggung jawab orang lain dengan meninggalkan aktivitas-aktivitas yang merupakan kemestian kehidupan sosial, dan yang lebih aneh, perlu diketahui bahwa sebagian dari mereka ini menampakan kejauhan dari dunia (Asketisme) sebagai perantara untuk memuaskan kecenderungan-kecenderungan duniawinya sendiri!
Dengan memandang apa-apa yang telah diutarakan, kita kembali kepada pertanyaan Anda dan menjadikan dua hal di bawah ini sebagai obyek kajian:
Dengan memperhatikan bahwa pakaian wol merupakan pakaian yang memiliki nilai yang terendah dalam abad pertama Islam, secara natural orang-orang yang berpenghasilan rendah yang menggunakan jenis pakaian ini. Menggunakan pakaian seperti ini, jika untuk memerangi [keinginan] jiwa dan memandang rendah haikat dunia maka tidaklah bermasalah. Berkaitan dengan ini, Abu Dzar Giffari, seorang ahli zuhud berkata, “Dengan memiliki dua lembar roti yang satu aku simpan untuk makan siang dan yang lain untuk makan malam, dan juga dua potong kain wol yang satu aku gunakan sebagai sarung dan yang lain diletakkan di pundak, apa urusanku dengan dunia?”[4]
Dia dengan ungkapannya ini, ingin menyampaikan poin penting kepada kaum muslimin bahwa dalam keadaan yang butuh bisa mencukupkan diri dalam batasan-batasan yang sangat minimal, tapi jangan sampai mengganti agama sendiri dengan dunia. Hal ini tidak bermakna bahwa dia mengharamkan pemanfaatan nikmat-nikmat Ilahi, karena kita tahu bahwa sekalipun pada masa kehidupan pengasingan Abu Dzar, dia dan keluarganya hidup dengan penghasilan dan pendapatan yang sangat minim.[5]
Jauh setelah masa kehidupan Abu Dzar, sekelompok dari kaum muslimin, dengan pandangan yang ekstrim meletakkan kezuhudan dan menjauhi dunia dalam batasan yang berlebihan dan menilai bahwa panampakan lahiriah kaum muslimin adalah menggunakan pakaian wol, bahkan para Imam Ahlulbait As dan para pembesar agama menjadi sasaran kritikan mereka karena tidak menerapkan model penampakan lahiriah seperti ini.[6]
Dengan kata lain, kezuhudan hakiki yang telah diajurkan oleh Islam telah dipropagandakan oleh para “penjual-kezuhudan” dan “pencari-murid”, dan dipahami atau tidak, telah terjebak ke dalam “pencari-dunia” yang secara lahiriah menjauhi dunia! Dengan mencermati bahwa istilah “tashawwuf” bersumber dari akar kata “shuf” yang berarti wol, perlahan-lahan, kelompok yang berpakaian wol ini dikenal dengan nama shufiyah [Sufisme] atau mutashawwifah dan aliran pemikiran mereka disebut tashawwuf (tasawuf).
Pada abad-abad belakangan, nama-nama seperti darwis, khurabati, dan lain sebagainya juga digunakan untuk memperkenalkan orang-orang seperti itu, dan istilah-istilah seperti khaneqâh (semacam tempat ibadah), mi, pir (orang-tua), qalandar, dan lain sebagainya juga dipandang memiliki posisi khusus dalam aliran mereka.
Dari satu sisi kita harus mengetahui bahwa ajaran-ajaran tasawuf tidak hanya cukup dengan berpakaian wol, melainkan di sepanjang masa, juga dilontarkan tolok ukur-tolok ukur perilaku lainnya oleh para syaikh dari aliran pemikiran ini kepada para pengikutnya yang sebagian darinya merupakan bidah-bidah yang tidak berpijak kepada ajaran agama. Namun terdapat juga amal-amal yang bersumber dari prinsip-prinsip al-Quran dan syariat.
Dalam koridor ini, terkadang perbuatan-perbuatan yang bersumber dari agama berubah menjadi suatu bidah karena telah mengalami perubahan! Seperti anjuran untuk ikhlas dalam amalan selama empat puluh hari yang dijelaskan dalam hadis[7] dan hasilnya adalah ketercerahan dan pencerahan batin. Namun para sufi formal, mengamalkannya dalam bentuk Chil Nesyini[8] dengan adab-adab khusus yang sebagian darinya tidak sesuai dengan ajaran suci syariat.
Walhasil, tasawuf berubah menjadi suatu gabungan dan kumpulan antara perilaku benar agama dan bidah salah spiritual.[9] Perkara inilah yang mengantarkan kepada suatu kesimpulan bahwa sebagian kaum Muslimin yang hanya mengamalkan bagian pertama [dari ajaran tasawuf yang sesuai dengan Islam] dan pensucian diri melalui perintah-perintah yang telah dianjurkan oleh Tuhan dan para Imam Ahlulbait, dikecam oleh sebagian fukaha dan menggolongkan mereka sebagai ke dalam lingkaran sufi dan darwis.
Dengan memperhatikan penjelasan di atas, dari satu sisi, walaupun sebagian ajaran-ajaran tasawuf seperti bentuk dan penampakan lahiriah tidak disandarkan kepada sumber-sumber keagamaan yang valid, namun tidak benar jika keseluruhan ajaran-ajaran tasawuf ditolak atau diterima secara seratus persen, melainkan harus dikaji setiap bagian-bagian ajarannya dan diteliti kesesuiannya dengan ajaran suci agama. Dari sisi lain, tidaklah benar kita menuduh setiap Muslim yang lebih menekankan dimensi-dimensi spiritual dan metode-metode pembersihan jiwa termasuk dalam kalangan para sufi.
Kita ketahui bahwa Imam Khomeini Qs adalah seorang yang melakukan metode suluk ruhani dan pembentukan diri spiritual dari sejak masa mudanya hingga akhir umurnya, karena itu bisa dilihat dalam ungkapan-ungkapan dan syair-syair beliau suatu pemikiran yang mirip dengan akidah dan istilah para sufi yang dalam pandangan pertama bisa disimpulkan bahwa beliau memiliki kecenderungan kepada maktab tasawuf, seperti dalam syair berikut ini:
Kasykul[10] fakir sebab kebanggaan kami
Wahai penolong hati yang tertipu, tambahkan kebanggaan…[11]
Atau:
Wahai orang tua, sampaikan kami ke Khaneqah[12]
Sahabat karib telah pergi, tunjukkanlah jalan[13]
Dan juga:
Sufi! Sucikan hati dari jalan cinta
Janji yang terucap harus terpenuhi[14]
Walaupun syair-syair ini dan istilah-istilah yang digunakan di dalamnya, bisa dikatakan cenderung kepada tasawuf, akan tetapi jangan cepat dihukumi dari satu sisi, melainkan dari sisi lain, perlu diperhatikan bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam ungkapan-ungkapan mengisyaratkan kepada suatu realitas dan hakikat yang mungkin tidak bisa diutarakan secara langsung dan jelas. Jika tidak demikian, kita ketahui bahwa di sepanjang kehidupan Imam Khomeini Qs, tidak pernah meletakkan [memikul] suatu kasykul di pundaknya atau mampir ke suatu Khâneqah. Dari aspek lain perlu diperhatikan ungkapan dan kata-kata lain beliau lalu melakukan penyimpulan terakhir. Dalam hal ini, terdapat syair-syair lain yang menjelaskan penentangan beliau terhadap Sufisme, seperti:
Sufi tak paham “penyatuan” kekasih
Saya tak ingin sufi yang tak suci[15]
Dan atau:
Saya buang cintamu dari lingkaran sufi
Hamba sufi, dengarkan kuletakkan dalam keledaiku[16]
Dan juga:
Kami perang dengan sufi, arif, atau darwis
Kami serang filsafat dan ilmu kalam (teologi)[17]
Secara lahiriah, syair-syair ini saling bertolak belakang, apa yang harus dilakukan? Pada akhirnya, apakah beliau menerima tasawuf atau menolaknya?
Dalam menjawab pertanyaan ini mesti dikatakan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pertama, kumpulan ajaran-ajaran tasawuf yang searah dengan syariat suci dimana seorang muslim sejati harus mengamalkannya dalam upaya pembentukan diri spiritual, adalah perkara-perkara yang disepakati oleh Imam Khomeini Qs dan menganjurkannya, “Kita harus meyakini apa [efek dan pengaruh yang ditimbulkan] dari munajat Tuhan kepada manusia, kita harus mengimani munajat itu, jangan kita mengingkarinya, jangan kita mengatakan bahwa semua ini adalah perkataan-perkataan para darwis (sufi). Semua hal ini ada dalam al-Quran dalam bentuknya yang lembut [sempurna] dan dalam kitab-kitab doa suci kita yang bersumber dari para Imam Ahlulbait As, semua perkara ini ada, namun tidak sesempurna dalam al-Quran, melainkan dalam bentuk yang cukup sempurna…semua orang yang menggunakan istilah-istilah ini setelahnya, mengetahui atau tidak terambil dari al-Quran dan hadis, adalah [walaupun] mungkin mereka memandang sanad-sanad utamanya tidak sahih.”[18]
Berdasarkan hal ini, dalam perspektif Imam Khomeini Qs, jangan khawatir dengan cap sufi atau merek darwis yang kemudian kita meninggalkan upaya-upaya pembentukan diri [pensucian batin dan pembersihan hati] spiritual, namun hal ini bukan bermakna bahwa beliau mengesahkan seluruh perbuatan dan perilaku para sufi.
Dalam sepucuk surat Imam Khomeini Qs yang kurang lebih ditulis puluhan tahun sebelum revolusi, selagi beliau masih muda, kita menyaksikan sebuah nasehat seperti ini, “Jangan ridha dengan ungkapan dan perkataan para pembesar formal tasawuf; jangan dengarkan klaim-klaim hiruk-pikuk para ahli khirqah (para sufi).”[19]
Sepuluh tahun setelahnya (tahun 1363 Syamsiah), setelah menjelaskan anjuran-anjuran tegasnya kepada anak beliau Hujjatul Islam dan Muslimin Sayid Ahmad dalam rangka pembentukan diri (pensucian batin), beliau berpesan bahwa apa-apa yang saya katakan adalah tidak bermakna bahwa dirimu tidak lagi berkhidmat kepada masyarakat, tatkala pergi bertapa (mengasingkan diri), dan menyerahkan segalanya kepada makhluk Tuhan [menjadikan diri sebagai beban masyarakat] yang hal ini merupakan sifat-sifat para jahil-religius[20] atau para darwis-penjaja.”[21]
Begitu pula dalam anjurannya kepada menantu perempuannya sendiri (istri Sayid Ahmad) terungkap demikian, “Saya tidak ingin mensucikan para pengklaim-pengklaim (sebagian sufi) itu yang mungkin layak masuk ke dalam api neraka, saya ingin kalian jangan mengingkari spiritualitas [aspek ruhani dan batin yang diklaim oleh para sufi] itu. Spiritualitas tersebut tidak lain adalah spiritualitas yang juga ditegaskan oleh al-Quran dan hadis, yang para penentangnya tidak memahaminya atau hanya mengerti secara awaw.”[22]
Imam Khomeini Qs mengkritik pandangan-pandangan yang ekstrim dan minor, dan menegaskan mizan dan tolok ukur diterimanya amal-perbuatan adalah niat-niat dan motif-motif ruhani setiap orang, dan bukan perilaku-perilaku khusus dan penampakan lahiriah, dalam suatu ungkapan beliau, “Anakku! Bukan pengasingan diri para sufi sebagai bukti kebersamaan dengan Tuhan, dan bukan bersama dengan masyarakat dan pembentukan negara adalah dalil keterpisahan dengan Tuhan, mizan dalam amal-perbuatan adalah motivasi-motivasi mereka, adalah sangat mungkin seorang abid [ahli ibadah] dan zahid [ahli zuhud] terjebak dalam tipuan Iblis.”[23]
Adalah tepat jika kita menyaksikan setiap perkataan beliau yang “berbau” tasawuf dan Darwisme, tidak semestinya kita menggolongkannya sebagai penegas atas dukungan kepada Sufisme dan Darwisme, melainkan kita meletakkannya dalam koridor perintah-perintah al-Quran dan Sunnah.
Referensi:
[1] . “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu berpikir?” (Qs. Al-An’am [6]: 32); “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya (dapat memanfaatkannya), tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berpikir.” (Qs. Yunus [10]: 24); “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main belaka. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.” (Qs. Ankabut [29]: 64); “Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.” (Qs. Muhammad [47]: 36); “Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (Qs. Al-Hadid [57]: 20), dan ratusan ayat-ayat lainnya.
[2] . “Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah, “Semua itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” (Qs. Al-A’raf [7]: 32); “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya semata kamu menyembah.” (Qs. Baqarah [2]: 168 dan 172); “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Qs Al-Maidah [5]: 88); “Dan Dia-lah yang menciptakan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma dan tanam-tanaman yang bermacam-macam rasa dan buahnya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Qs. Al-An’am [6]: 141); “Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Qs. Al-Mulk [67]: 15); dan ayat-ayat lainnya.
[3] . “Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (Qs. Baqarah [2]: 201).
[4] . Kulaini, Muhammad Ya’qub, al-Kâfi, jil. 2, hal. 134, Hadis 17, Dar al-Kutub Islamiyah, Teheran, 1365 S.
[5] . Majlisi, Muhammad Baqir, Bihâr al-Anwâr, jild. 22, hal. 429, hadis 37, Muassasah Al-Wafa’, Beirut, 1404 H.
[6] . Al-Kâfi, jil. 5, hal. 65, Hadis 1.
[7] . Al-Kâfi, jil. 2, hal. 16, Hadis 6.
[8] . Duduk selama empat puluh hari dengan adab-adab khusus.
[9] . Untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kemunculan dan perkembangan tasawuf, rujuklah ke kitab seperti Jasteju dar Tasawuf Irân ditulis oleh Dr. Abdul Husain Zarin Kub.
[10] . Suatu wadah yang terbuat dari tembaga yang kurang lebih berbentuk kerucut yang diikatkan pada sebuah tongkat. Bejana ini dipikul oleh para sufi yang digunakan untuk “mengemis” kepada orang lain.
[11] . Bodey-e ‘Isyq, hal. 40, Muassasah Tanzhim wa Nasyr-e Atsar-e Imam Khomeini, Tehrean, 1368 S.
[12] . Semacam tempat peribadatan, penyelenggaraan acara-acara resmi, pertemuan, dan perjamuan para sufi.
[13] . Bodey-e ‘Isyq, hal. 77.
[14] . Shahifah Imâm, jil. 18, hal. 444, Muassasah Tanzhim wa Nasyr-e Atsar-e Imam Khomeini, Teheran, 1386 S, Cetakan Keempat.
[15] . Bodey-e ‘Isyq, hal. 29.
[16] . Ibid, hal. 33.
[17] . Ibid, hal. 55.
[18] . Shahifah Imâm, jil. 17, hal. 458.
[19] . Ibid, jil. 1, hal. 18
[20] . Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup seraya menampak-nampakkan kezuhudan dan ketakwaan.
[21] . Ibid, jil. 18, hal. 511.
[22] . Shahifah Imâm, jil. 18, hal. 453,
[23] . Ibid, jil. 18, hal. 512.
(Study-Syiah/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)